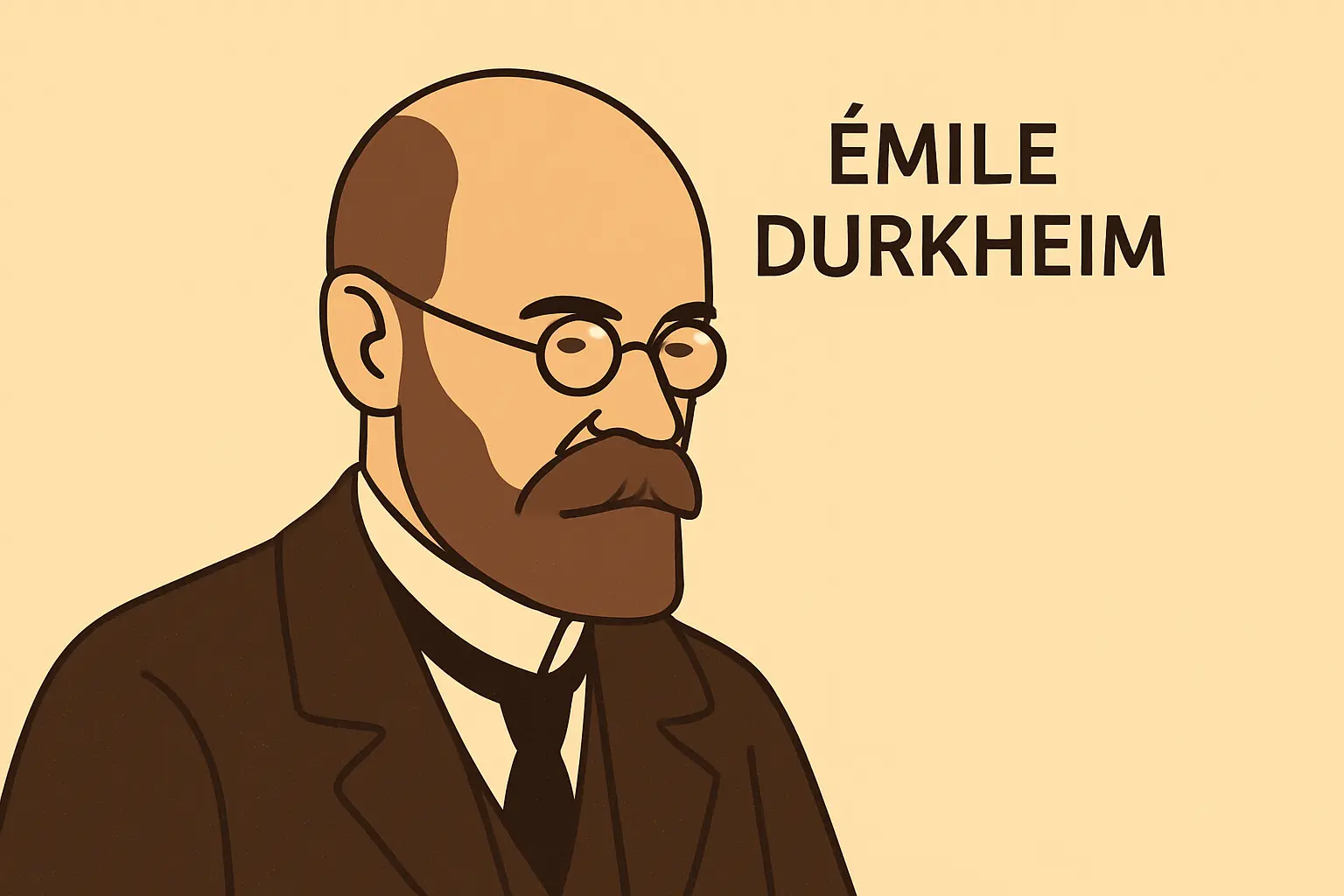Relasi yang Renggang: Ketika Kedekatan Sekadar Ilusi dan Jarak Menjadi Rumah Baru

Kita hidup di masa yang aneh: orang-orang paling mudah dihubungi justru adalah mereka yang paling sulit benar-benar “ditemui.” Kita punya ratusan kontak, puluhan grup WhatsApp, dan timeline yang selalu ramai, tetapi nyaris tak ada ruang untuk satu obrolan mendalam tanpa distraksi. Aneh, tapi lumrah. Dekat tapi menjauh. Renggang tapi pura-pura erat.
Relasi sosial hari ini ibarat tali karet—lentur, bisa ditarik sejauh mungkin, dan tak jarang kembali memukul kita tepat di wajah.
Fenomena relasi yang merenggang sebenarnya bukan hal baru. Ia hanya semakin kasat mata. Kita melihatnya dalam hubungan keluarga, pertemanan, bahkan dalam komunitas yang katanya “solidaritas nomor satu.” Kita saling mengikuti di media sosial, tapi tak lagi saling memahami. Kita tahu kabar terbaru dari story Instagram, tapi tak tahu kabar batin satu sama lain. Kita saling melempar emoji, tapi hati kita sudah pindah rumah entah ke mana.
Lantas, kenapa relasi kita terasa makin renggang, padahal sarana untuk terhubung semakin banyak?
Relasi yang Digerus Rutinitas: Sibuk yang Sebenarnya Tidak Selalu Penting
Kalau dulu alasan menjauh adalah jaga jarak, hari ini alasannya “maaf, lagi sibuk.” Kalimat pamungkas yang seringkali benar hanya setengahnya. Bukan berarti kita tidak punya kesibukan, tapi sering kali kesibukan itu diisi hal-hal yang—kalau mau jujur—bukan prioritas. Kita sibuk membalas email, menyelesaikan kerjaan dadakan, men-scroll TikTok satu jam tanpa sadar—sementara konversasi dengan sahabat lama kita tunda sampai besok. Lalu besok kita tunda lagi. Lama-lama hilang.
Rutinitas modern membuat pertemuan tidak lagi spontan. Semua harus dijadwalkan, sementara hidup kita sendiri tidak pernah benar-benar punya jadwal yang stabil.
Masalahnya, hubungan manusia tidak mengenal appointment. Ia tumbuh dari momen acak, dari nongkrong tanpa agenda, dari bercanda tanpa rencana, dari obrolan yang berawal dari “lagi apa?” dan berakhir pada diskusi eksistensial. Kini, ruang-ruang kecil seperti itu semakin menghilang.
Kita sibuk. Atau pura-pura sibuk. Tapi yang jelas, relasi kita ikut terseret arusnya.
Algoritma yang Memilihkan Teman
Suka tidak suka, algoritma juga punya saham besar dalam renggangnya relasi manusia. Ia menentukan siapa yang sering muncul di timeline kita, siapa yang lenyap diam-diam, siapa yang tampak akrab padahal kita bahkan jarang berinteraksi.
Ironisnya, kita bisa lebih dekat dengan seseorang hanya karena sering melihat mereka di feed, bukan karena kita benar-benar menjalin hubungan. Algoritma memperkuat bias bahwa yang sering terlihat adalah yang penting.
Padahal kadang yang jarang muncul justru adalah orang-orang yang dulu paling dekat. Kita tidak lagi melihat mereka, maka mereka pun tenggelam dari jangkauan pikiran.
Bukan karena kita tidak peduli—tapi karena sistem mendesain kita untuk lupa.
Normalisasi Jarak Emosional
Hari ini, menjaga jarak bukan hanya pilihan, tapi mekanisme bertahan hidup. Kita mulai terbiasa menyimpan isi hati sendiri karena takut dianggap lebay, drama, atau tidak dewasa. Kita memilih aman daripada rentan. Kita memilih emoji 😂 daripada curhat sungguhan.
Sosial media juga tidak membantu. Semua orang berlomba menjadi “yang paling baik-baik saja.” Tidak ada yang ingin tampak rapuh. Tidak ada yang ingin menjadi beban. Maka kita tutup pintu pelan-pelan, sampai akhirnya lupa cara membukanya kembali.
Jarak emosional menjadi normal. Renggang bukan lagi tanda bahaya—ia menjadi gaya hidup.
Hubungan Tanpa Investasi: Serba Cepat, Serba Instan
Relasi yang kuat butuh usaha: waktu, konsistensi, perhatian, dan kehadiran. Sayangnya, budaya instan mengubah cara kita menjalin hubungan. Kita ingin kedekatan yang cepat, intens, dan tidak merepotkan.
Kita ingin orang lain mengerti tanpa dijelaskan. Kita ingin hubungan yang selalu asyik tanpa konflik. Kita ingin kehangatan tanpa perlu repot-repot menyalakan apinya.
Padahal hubungan tidak bekerja seperti itu. Ia tidak bisa dibangun hanya dari chat singkat dan reaction emoji. Ia butuh pertemuan nyata—atau minimal, percakapan yang jujur.
Relasi yang renggang sering bukan karena konflik besar, tapi karena absenya investasi kecil yang seharusnya kita rawat setiap hari.
Ketakutan untuk Menghubungi Duluan
Lucunya, sebagian relasi renggang bukan karena dua orang saling menjauh, tapi karena dua-duanya sama-sama menunggu. Ada rasa sungkan untuk memulai obrolan. Ada rasa malu karena sudah terlalu lama tidak berkomunikasi. Ada rasa takut terlihat “butuh.”
Padahal seringkali, satu pesan sederhana bisa menghidupkan kembali hubungan yang sempat mati suri.
Tapi ego membuat kita menahan diri. Kita menunggu. Dan orang di seberang menunggu juga. Lama-lama yang ditunggu bukan kabar, melainkan akhir.
Lalu, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Relasi yang renggang sebenarnya tidak harus berakhir. Renggang hanyalah tanda bahwa ada jarak yang belum diisi. Dan jarak, kalau dipenuhi dengan usaha kecil tapi konsisten, bisa menyempit kembali.
Beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan:
-
Kirim pesan spontan tanpa alasan
-
Ajak ngobrol tentang hal remeh dulu
-
Jangan menunggu momen “sempurna” untuk menghubungi
-
Jujur ketika merasa jauh
-
Hargai waktu yang orang lain berikan
-
Kurangi ekspektasi kedekatan instan
Kedekatan bukan hadiah, tapi proses. Dan seperti semua proses, ia butuh dimulai.
Penutup: Renggang Bukan Kalah
Pada akhirnya, semua hubungan pasti melalui fase renggang. Itu normal. Yang tidak normal adalah ketika kita membiarkannya menjadi permanen tanpa berusaha memahami penyebabnya.
Relasi yang renggang bukan berarti kita gagal sebagai manusia sosial. Ia justru mengingatkan kita bahwa kedekatan membutuhkan ruang, waktu, dan keberanian untuk muncul kembali setelah lama hilang.
Kalau hari ini ada seseorang yang terasa jauh, mungkin bukan karena ia menjauh. Mungkin hanya karena dunia terlalu bising, terlalu cepat, dan terlalu penuh distraksi.
Dan di tengah semua keramaian itu, kita hanya perlu satu langkah kecil untuk mulai mendekat lagi.

 Budaya Internet
Budaya Internet Emosi Digital
Emosi Digital Media Sosial
Media Sosial Refleksi Sosial
Refleksi Sosial Sosiologi Digital
Sosiologi Digital Tokoh Sosiologi
Tokoh Sosiologi